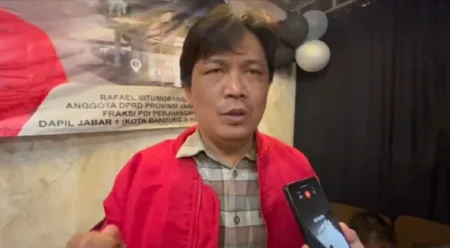bukamata.id – Jumat pagi, 6 Februari 2026, kawasan Gedung Sate, Bandung, tidak menyuguhkan pemandangan birokrasi yang lazim. Deru mesin dari sekitar 30 truk tronton memecah keheningan Jalan Diponegoro, menciptakan benteng besi yang seolah mengepung pusat kekuasaan Jawa Barat. Kendaraan-kendaraan raksasa itu membeku, mesin dimatikan, namun pesan yang dibawa para pengemudi dan buruh tambang itu jauh lebih bising daripada raungan klakson: mereka sedang sekarat.
Pemandangan ini adalah kulminasi dari ketegangan yang meruncing sepanjang tahun. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melancarkan operasi “Sapu Jagat”. Sebuah langkah agresif untuk menertibkan sektor pertambangan yang selama ini dianggap liar dan merusak. Namun, di balik narasi pelestarian lingkungan, tersimpan jeritan ribuan perut yang terancam kosong.
Antara Penertiban dan “Vonis Mati” Ekonomi
Data di atas kertas menunjukkan urgensi tindakan pemerintah. Sepanjang 2025, tercatat ada 176 titik tambang ilegal yang menggerogoti perut bumi Jawa Barat. Langkah represif tak terelakkan. Sebanyak 118 lokasi telah digembok mati, sementara 58 sisanya tengah diseret ke meja hijau.
“Yang ada di Jabar totalnya 176 tambang ilegal,” tegas Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah representasi dari kerusakan ekologis, longsor, dan jalanan yang hancur.
Namun, kebijakan yang dipukul rata seringkali memakan korban yang tak bersalah. Di tengah aksi massa, Yadi Suryadi, koordinator aksi yang mewakili asosiasi seperti ATTN, ATTB, dan SBNI, menyuarakan kepedihan mereka. Kelompok ini tidak membela tambang liar. Mereka justru merasa menjadi korban “peluru nyasar” dari regulasi yang tumpang tindih.
Mereka memprotes serangkaian aturan—mulai dari Pergub No. 11/2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan hingga surat edaran moratorium lingkungan—yang dianggap menciptakan ketidakpastian hukum. Bagi pengusaha legal, ketidakjelasan kapan moratorium berakhir sama saja dengan pembunuhan perlahan terhadap usaha mereka.
“Terkait aksi hari ini kita datang ke sini untuk meminta agar supaya dicabut yang katanya sementara (kebijakan moratorium), tapi tidak ada keputusan sementara itu sampai kapan? Di sini banyak masyarakat yang dirugikan,” ujar Yadi dengan nada tinggi.
Lebih teknis lagi, pembatasan jenis kendaraan sumbu 3 lewat Surat Edaran ESDM No. 5126/ES.09 dianggap tidak masuk akal bagi transporter yang sudah terlanjur berinvestasi armada besar. “Yang memiliki kendaraan sumbu 3, tidak ada penghasilan keluarganya karena terhentinya kegiatan usaha,” tambah Yadi.
Kompensasi: Gula-gula di Tengah Pahitnya Realita
Ketika dapur warga mulai dingin akibat penutupan tambang, pemerintah mencoba hadir dengan “obat penenang” berupa kompensasi sosial. Fokus utama tertuju pada Kabupaten Bogor—khususnya kawasan Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg—yang selama ini menjadi episentrum konflik tambang galian C.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi, mengumumkan alokasi dana jumbo sebesar Rp45 miliar. Dana ini ditargetkan untuk 15.293 Kepala Keluarga (KK) yang belum menerima hak mereka sejak Desember 2025.
“Yang 2.938 KK mereka sudah. Yang 15.000 belum. Jadi kami akan fokus dulu, tuntaskan yang seharusnya Desember mendapat bantuan, yang 15 ribu KK itu. 15 ribu di kali Rp3 juta, total sekitar Rp45 miliar,” ungkap Ade, Rabu (14/1/2026).
Namun, realisasi di lapangan tak secepat laju truk tambang. Birokrasi yang berbelit membuat ribuan warga harus menunggu proses verifikasi yang panjang, mulai dari tinjauan Inspektorat hingga penetapan Keputusan Gubernur. Ade mengakui, saat ini fokus pemerintah baru sebatas melunasi tunggakan satu bulan. Nasib kompensasi untuk bulan Januari dan Februari 2026 masih menunggu hitung-hitungan kas daerah.
“Jadi sekarang fokusnya satu bulan dulu yang 15 ribu itu,” ucap Ade jujur. Ia meminta warga untuk tidak panik dan tidak terprovokasi isu miring. “Jangan khawatir, karena Pemprov tidak mungkin meninggalkan yang 15 ribuan itu dan hanya menyelesaikan yang 2.938 KK.”
Pertanyaannya kemudian muncul: cukupkah Rp3 juta untuk menggantikan mata pencaharian yang hilang permanen? Bagi banyak pengamat, ini hanyalah solusi jaring pengaman sementara (safety net) yang rapuh, bukan solusi struktural.
Bedah Kasus: Efek Domino Ekonomi Mikro
Krisis ini memantik analisis tajam dari kalangan akademisi. Putri Diesy Fitriani, SE.Sy., ME, Dosen Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melihat fenomena ini sebagai guncangan hebat bagi ekonomi mikro. Dampaknya tidak hanya direct (langsung) kepada penambang, tetapi juga indirect (tidak langsung) ke sektor pendukung.
“Banyak dari buruh tambang, supir, operator alat berat dan pekerja lainnya yang menggantungkan hidupnya pada sektor tambang ilegal tersebut,” jelas Putri. Ia menambahkan, “Hal inipun memiliki efek berantai, seperti para pedagang toko sembako, toko makanan, bengkel bahkan kos-kosan yang menyebabkan daya beli menjadi turun drastis.”
Putri menyarankan legalisasi bersyarat sebagai jalan tengah. Menurutnya, tambang ilegal memang memberikan uang cepat, tapi rapuh. Legalisasi akan mengubahnya menjadi pendapatan yang lebih pasti dan berkelanjutan, sehingga daya beli masyarakat tidak fluktuatif. “Kuncinya ada pada desain kebijakan agar sederhana, terjangkau, dan betul-betul berpihak pada masyarakat sekitar,” tegasnya.
Di sisi lain, Pakar Ekonomi Universitas Islam Nusantara (Uninus), Dr. Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, menyoroti aspek iklim investasi. Kebijakan yang terkesan “kaget-kagetan” adalah musuh bagi investor.
“Biasanya investor itu paling sensitif terhadap ketidakpastian aturan. Kalau penutupan terlihat mendadak atau tidak jelas alasannya, investor bisa menahan diri,” kata Rizaldy. Namun, ia sepakat bahwa dalam jangka panjang, ekonomi tidak bisa bertumpu pada kerusakan alam. “Lingkungan rusak justru mahal secara ekonomi. Jadi kuncinya bukan menghentikan ekonomi, tapi mengelolanya dengan bijak.”
Gubernur Mencari Titik Temu
Menyadari situasi yang kian pelik, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) berencana mengambil langkah taktis. Ia dijadwalkan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemilik tambang hingga kontraktor pembangunan, di satu meja.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya membedah “kebohongan-kebohongan” data yang selama ini terjadi. Dedi menyoroti modus operandi di mana izin yang dikantongi tidak sesuai dengan fakta lapangan.
“Di izin tambangnya misalnya 10 hektare tapi nambangnya 40 hektare. Di izinnya di lokasi A tapi lokasi nambangnya di lokasi C. Kan ini problem,” tegas Dedi di Hotel Holiday Inn, Bandung, Kamis (22/1/2026).
Langkah KDM ini bertujuan untuk menciptakan transparansi data kebutuhan material pembangunan. Dengan mempertemukan kontraktor dan penambang, pemerintah ingin memutus rantai pasok ilegal. “Kita sudah bisa menghitung kebutuhan pembangunan ini, sehingga menghitung pajaknya sudah bisa dari sekarang. Jadi tidak ada lagi kebohongan,” paparnya.
Lebih jauh, Dedi melontarkan wacana reformasi pajak yang radikal untuk meredam ketimpangan sosial. Ia menginginkan agar daerah penghasil tambang menikmati kue pembangunan yang lebih besar.
“Rumusan pajak, bahwa hasil pajaknya tentukan saja misalnya 60 persen harus kembali untuk desa di mana tambang berada sehingga infrastrukturnya baik, pendidikannya baik, rumah rakyatnya baik,” cetus Dedi.
Simpang Jalan
Jawa Barat kini berdiri di persimpangan krusial. Di satu sisi, ketegasan pemerintah menutup tambang ilegal adalah langkah mutlak demi menyelamatkan lingkungan dari kehancuran total. Di sisi lain, ribuan warga di Rumpin, Parungpanjang, dan sekitarnya kini hidup dalam ketidakpastian, menanti kucuran dana kompensasi yang birokrasinya berliku, sembari berharap izin usaha mereka kembali diterbitkan.
Apakah pertemuan pekan depan akan menjadi titik balik rekonsiliasi, atau sekadar formalitas di tengah badai protes? Yang jelas, publik menanti bukti nyata: bahwa ambisi melestarikan alam tidak harus dibayar dengan memiskinkan rakyatnya sendiri. Seperti kata Yadi Suryadi di tengah kepulan asap knalpot truk, “Ini sudah ada penelitian tidak akan ada bencana kalau diatur.”
Kesimpulan
Kisah penertiban tambang di Jawa Barat ini bukan sekadar cerita hitam-putih tentang penegakan hukum melawan kejahatan lingkungan. Ini adalah drama kompleks tentang bagaimana negara menyeimbangkan neraca ekologi yang rusak parah dengan neraca ekonomi rakyat yang rapuh.
Operasi “Sapu Jagat” mungkin berhasil memulihkan bentang alam Pasundan dari lubang-lubang menganga, namun ia meninggalkan lubang lain yang tak kalah dalam di dompet ribuan warganya. Dana kompensasi Rp45 miliar yang disiapkan pemerintah, meski bernilai fantastis, hanyalah “napas buatan” sementara. Ia mungkin mampu menyambung hidup untuk satu atau dua bulan, namun tidak akan pernah bisa menggantikan martabat kemandirian ekonomi yang hilang akibat birokrasi yang lamban dan regulasi yang dipukul rata.
Rencana Gubernur Dedi Mulyadi untuk mendudukkan semua pihak di satu meja adalah pertaruhan terakhir. Jika pertemuan itu hanya menghasilkan retorika normatif tanpa solusi teknis—seperti kejelasan zonasi legalisasi, percepatan jalan tambang, dan reformasi pajak yang adil bagi desa—maka gejolak sosial di Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg hanyalah permulaan.
Pada akhirnya, keberhasilan transisi ini tidak akan diukur dari seberapa banyak tambang yang ditutup atau seberapa hijau bukit yang direklamasi. Ia akan diukur dari seberapa mampu pemerintah membuktikan bahwa menjaga alam tidak harus dilakukan dengan mematikan dapur rakyatnya sendiri. Jawa Barat kini menunggu: apakah kebijakan ini akan menjadi tonggak peradaban baru yang lestari, atau justru menjadi monumen kegagalan yang memicu kemiskinan struktural baru? Waktu—dan perut rakyat—tidak bisa menunggu terlalu lama.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News