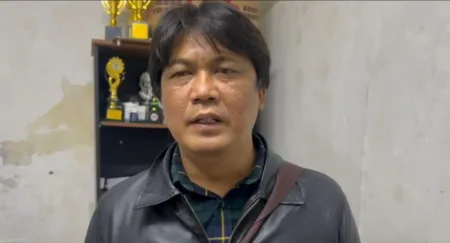bukamata.id – Sebuah ekspedisi ilmiah di hutan hujan Sumatera Barat yang seharusnya menjadi perayaan kolaborasi riset internasional justru berubah menjadi polemik yang ramai dibicarakan publik Indonesia. Universitas Oxford, kampus bergengsi dari Inggris, tengah menjadi sorotan tajam setelah unggahan media sosialnya dinilai mengabaikan kontribusi peneliti Indonesia dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasseltii. Kritik datang bukan hanya dari warganet, tetapi juga dari akademisi hingga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Kasus ini bermula dari ekspedisi gabungan antara peneliti Oxford dan peneliti lokal Indonesia. Salah satu tokoh yang terlibat adalah Chris Thorogood, ilmuwan dari Oxford Botanic Garden yang dikenal aktif meneliti flora langka. Melalui ekspedisi yang berlangsung beberapa waktu lalu, tim lintas negara ini berhasil menemukan bunga Rafflesia hasseltii yang sedang mekar — sebuah momen yang sangat jarang terjadi dan sering dianggap sebagai “hadiah alam”.
Dalam unggahan pribadinya yang penuh antusiasme, Chris menuliskan pengalaman mereka menembus hutan Sumatera yang terkenal sulit dijangkau. “Kami menemukannya! Kami berjalan siang dan malam menembus hutan hujan Sumatera yang dijaga harimau dan hanya bisa diakses dengan izin khusus demi ini, Rafflesia hasseltii. Hanya sedikit orang yang pernah melihat bunga ini, dan kami menyaksikannya mekar pada malam hari. Ajaib,” tulisnya.
Unggahan ini sempat menuai pujian dari pecinta botani dan publik internasional. Namun, sorotan berubah arah ketika akun resmi Universitas Oxford membagikan temuan yang sama, tetapi dengan narasi berbeda. Alih-alih menonjolkan kerja sama lintas negara, unggahan tersebut justru fokus pada peran peneliti mereka sendiri.
Dalam postingan di platform X dikutip Selasa (25/11/2025), Oxford menulis: “Rafflesia hasseltii: A plant seen more by tigers than people. Yesterday, Oxford Botanic Garden’s @thorogoodchris1 was part of a team that trekked day and night through tiger-patrolled Sumatran (an island in Indonesia) rainforests to find Rafflesia hasseltii.”
Yang menjadi masalah, unggahan itu sama sekali tidak menyebut tiga peneliti Indonesia yang terlibat dalam ekspedisi: Joko Witono, Septi Andriki, dan Iswandi. Padahal, dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa proses penemuan bunga ini tak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan lokal dan kerja keras tim dari Indonesia.
Ketidakhadiran nama mereka dalam unggahan institusi sebesar Oxford memicu reaksi cepat dari warganet Indonesia. Kritik mengalir deras, sebagian menilai bahwa tindakan itu menggambarkan bias kolonial dalam dunia riset internasional — sesuatu yang masih sering dibicarakan dalam dinamika akademik global.
Kritik publik semakin menguat ketika Anies Baswedan ikut menyampaikan tegurannya. Dalam unggahan di akun media sosial, ia menulis pesan langsung untuk Oxford: “Dear @UniofOxford, our Indonesian researchers, Joko Witono, Septi Andriki, and Iswandi, are not NPCs. Name them too,” tulisnya.
Kalimat itu menjadi pemantik yang membuat diskusi semakin meluas. Banyak yang menilai masalah ini bukan sekadar soal penyebutan nama, tetapi soal penghargaan terhadap kontribusi ilmiah dari negara berkembang yang sering dianggap berada di posisi “pembantu riset”, bukan mitra sejajar.
Tidak sedikit komentar yang bernada sinis. Ada warganet yang menyebut respons Oxford sebagai tindakan “typical colonizers”. Komentar lain mengingatkan bahwa Indonesia tak perlu mencari validasi dari “institusi bekas penjajah.” Kritik ini memperlihatkan betapa isu representasi dan pengakuan ilmiah menjadi sangat sensitif dalam konteks hubungan negara maju dan berkembang.
Namun, tak semua komentar bernada marah. Sebagian warganet menuturkan pengalaman personal terkait penelitian Rafflesia. Misalnya, ada yang menceritakan bagaimana ia pernah mendampingi orang tua meneliti bunga tersebut di Kalimantan dan memahami betapa sulitnya menemukan tanaman yang hanya mekar dalam kondisi tertentu. Warganet lain mengingatkan bahwa dalam video ekspedisi, tampak keterlibatan warga lokal seperti seseorang yang mereka sebut “Pak Iwan”, yang diduga merupakan orang pertama yang mengetahui keberadaan Rafflesia hasseltii tersebut. Ungkapan ini menjadi pengingat bahwa dokumentasi lapangan kerap dimulai dari kontribusi masyarakat adat dan lokal yang jarang mendapat sorotan.
Di sisi lain, terdapat juga kelompok warganet yang mencoba meredam tensi. Mereka berpendapat bahwa publik Indonesia tidak perlu bereaksi berlebihan, dan menyarankan agar lembaga riset nasional seperti BRIN lebih aktif mempublikasikan temuan serupa secara independen. Menurut mereka, jika narasi riset dikelola oleh institusi dalam negeri, pengabaian kredit ilmiah dapat diminimalkan.
Uniknya, perbedaan narasi antara unggahan Chris Thorogood dan akun resmi Oxford justru memperkeruh situasi. Dalam unggahan pribadinya, Chris sebelumnya sudah mencantumkan nama ketiga peneliti Indonesia secara lengkap, menunjukkan bahwa ia sendiri tidak mengabaikan kontribusi mereka. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan publik: mengapa akun resmi Oxford tidak melakukan hal serupa? Apakah ini sekadar kelalaian, atau ada standar editorial yang berbeda?
Perdebatan mengenai kredit ilmiah ini membuka diskusi lebih luas mengenai etika riset internasional. Dalam kerja kolaboratif lintas negara, pemberian kredit bukan hanya soal formalitas, tetapi simbol penghargaan yang mencerminkan kesetaraan. Kasus Oxford vs peneliti Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana satu unggahan dapat memantik diskusi tentang representasi, kekuasaan simbolik institusi besar, dan pentingnya mengakui kontribusi pihak lokal yang menjadi kunci keberhasilan penelitian lapangan.
Hingga kini, publik Indonesia masih menantikan klarifikasi atau revisi unggahan dari Universitas Oxford. Namun apa pun langkah selanjutnya, perdebatan ini telah memberikan satu pelajaran penting: kolaborasi ilmiah tidak akan bermakna tanpa penghargaan yang setara kepada semua pihak yang terlibat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News