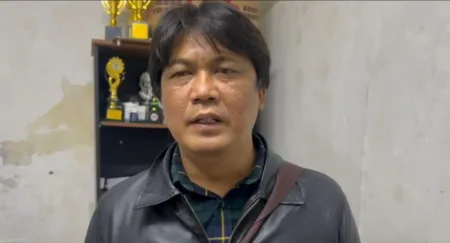LANGIT di atas Alun-Alun Garut, Jumat sore itu, tak menunjukkan tanda akan turunnya hujan. Tapi awan kelabu bergelayut, seolah tahu bahwa hari itu bukan akan diwarnai tawa, melainkan tangis. Ribuan orang berkumpul di pelataran Lapangan Oto Iskandar Dinata, menjawab undangan sebuah pesta rakyat yang dibalut dalam nuansa syukuran pernikahan anak pejabat daerah. Namun, apa yang mestinya jadi perayaan, justru berubah menjadi peristiwa memilukan: tiga nyawa melayang, termasuk seorang anak dan seorang anggota kepolisian.
Bukan karena bencana alam. Bukan pula karena musibah yang tak bisa diprediksi. Tragedi ini terjadi di tengah hiruk-pikuk perayaan yang semestinya mengusung sukacita. Ironisnya, pesta itu diklaim digelar untuk rakyat. Namun, justru rakyat pula yang menjadi korban.
Di tengah sorotan lampu dan suara panggung, ada hal yang luput: perencanaan yang matang, pengamanan yang memadai, dan—yang terpenting—empati. Ribuan orang berdesakan demi sebungkus nasi kotak. Dalam euforia yang tidak terkelola, panggung kebahagiaan berubah menjadi simbol kepongahan.
Sementara masyarakat diminta berhemat demi efisiensi anggaran negara, acara megah seperti ini tetap digelar. Ada yang bertanya lirih: “Apakah efisiensi tak berlaku jika yang berpesta adalah penguasa?” Sebab sesungguhnya, efisiensi sejati adalah mencegah kesia-siaan—terutama jika yang hilang adalah nyawa manusia.
Di tengah duka, muncul pula pernyataan tentang bantuan uang duka. Nilai yang disebutkan: Rp150 juta per keluarga korban. Tapi benarkah lembaran uang bisa menjadi pelipur bagi kehilangan seorang anak? Seorang ayah? Seorang saudara? Mungkin tidak. Sebab, kehilangan tak bisa ditakar dalam nominal.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi bagian dari narasi ini. Ia menyebut dirinya tidak mengetahui bahwa pesta pernikahan putranya, Maula Akbar Mulyadi Putra, dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, akan melibatkan masyarakat dalam skala besar. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dan berjanji akan mengambil pelajaran dari kejadian ini.
“Saya tidak tahu akan ada acara makan bersama dengan warga dalam skala sebesar itu,” ujarnya. Meski tak terlibat langsung, ia menegaskan tanggung jawab moralnya sebagai orang tua dan sebagai kepala daerah.
Namun, kata maaf, meski tulus, tak serta-merta menghapus luka yang terlanjur menganga. Yang dibutuhkan bukan hanya klarifikasi, tapi langkah konkret: pertanggungjawaban hukum, moral, dan politik. Karena rakyat bukan ornamen acara. Mereka bukan massa bayaran untuk foto-foto, bukan latar belakang bagi panggung kekuasaan.
Dalam budaya Sunda, kata Dedi suatu waktu, “Teu ilahar urang ngondang batur keur antri dahareun.” Tapi di tengah pesta itu, kita justru menyaksikan warga berebut makanan hingga meregang nyawa. Di mana letak nilai silih asah, silih asih, silih asuh ketika yang tersisa hanyalah pemandangan kamera, panggung, dan tenda-tenda mewah?
Rantang-rantang yang dulu dikirim dari rumah ke rumah dalam kehangatan gotong royong, kini digantikan dengan panggung megah yang dingin dan asing. Pesta telah selesai, tapi Garut belum benar-benar bangkit. Duka masih menyelimuti, dan seluruh Jawa Barat ikut berkabung.
Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Sebab kekuasaan, tanpa empati, hanya akan menghasilkan jarak. Dan ketika jarak itu menjadi jurang, rakyatlah yang paling dulu jatuh.
Hari ini, lebih dari apapun, masyarakat menanti ketegasan. Bukan sekadar belasungkawa. Tapi langkah nyata yang menunjukkan bahwa nyawa manusia tak pernah sepadan dengan panggung popularitas.
Sebab lebih baik satu pesta dibatalkan, daripada satu nyawa dikorbankan. Apalagi tiga.
Penulis adalah Redaktur Pelaksana (Redpel) bukamata.id
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News